Aku terbangun kala sakit itu kembali. Merayapi leher sampai ke seluruh jengkal tubuhku. Setiap kedipan yang kulakukan untuk memfokuskan pandangan, semakin mengundang semangat sang lara untuk menyiksaku. Mataku berair, cairannya berkumpul di ekor mata, menunggu giliran untuk jatuh menyusuri pelipis.
Tak pernah aku merasakan sakit sepedih ini.
Otak dalam tempurung kepala ini, mogok untuk bekerja. Yang dia lakukan cuma, menerjemahkan rasa sakit. Kalau dipikir-pikir, ini kali keduanya aku merasakan ini–sakit berkepanjangan. Yang pertama kali, sekitar dua minggu lalu dan yang kuingat, itu tak lama, cuma sepuluh menit. Tapi entah kenapa kali ini rasanya seperti berjam-jam. Entah memang lama atau orientasi waktuku memudar.
Aku mencoba membunuh waktu dengan menekuri langit-langit kamar di atas sana, mengabaikan ilusi kalau benda datar itu ingin menimpaku dengan bobotnya. Tak terlewat seinci pun mataku menyapu permukaan putih nan mulus itu. Kemudian satu kenyataan menamparku telak. Langit kamarku tidak berwarna putih, bahkan tidak dicat sekalipun. Warnanya silver khas dinding logam yang di beberapa bagian sudah berkarat.
Di mana aku?
Penderitaanku bertambah saat entah dari mana, sebuah tangan kurus merengkuh tubuhku. Sakitnya semakin beranak pinak. Walau sulit, kupaksakan kepalaku untuk menoleh, mempersetankan rasa sakit dan rintihan yang tak sadar kusuarakan. Adalah sebuah wajah menyeramkan yang kudapati. Dilihat dari penampilannya, dia laki-laki. Kepalanya diselimuti rambut merah agak pendek.
Sungguh sial, otakku menemukan pekerjaan baru yaitu berfikir ...
Apa aku diclik? Lagi? Kenapa harus aku yang diculik?
****
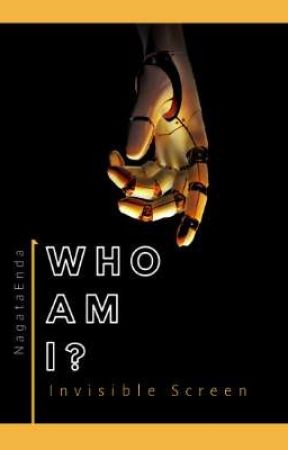
YOU ARE READING
Who Am I? Invisible Screen
Science FictionNamanya menjadi sependek potongan sosis di kantin. Dia tak punya keluarga, apalagi marga. Pulangnya bukan kembali ke rumah hangat yang ramai akan anggota keluarga, tapi naik lift kemudian masuk ke kamar yang cuma 3x4 meter luasnya. _________________...
