Aku masih ingat saat dia menendang mukaku dengan kakinya yang ramping, tetapi meski begitu, rasanya semenyakitkan saat wajahku terbentur pintu besi kamar. Aku juga mengingat jelas sensasi saat dia berhasil melukai bahuku, membuatku refleks menangkupkan tangan ke sana. Aneh, sudah tidak sakit. Apakah aku benar-benar terdampar selama berminggu-minggu di kamar dua cowok itu sampai lukaku sembuh sendiri? Entahlah, yang pasti, rasanya aku ingin mencabut pintu kamar siapa pun lalu menghantamkan benda itu ke wajah si senior.
Aku tidak tahu alasan dia menyerangku waktu itu, barangkali dia punya dedam pribadi denganku atau apa, tapi yang pasti, semenjak dia melakukan itu, aku termotivasi untuk menumbuhkan dendam kesumat untuknya. Dia kira aku ini orang baik yang bisa memaafkan perbuatannya begitu saja? Atau dia mungkin mengira aku sudah mati sampai-sampai dia terlihat terkejut saat pertama kali mata kami bertemu.
Mereka berjalan dengan lumayan cepat sebenarnya, tapi dalam sudut pandangku, itu seperti sebuah slow motion. Masih dengan berpegangan ke dinding, aku akhirnya tersaruk mundur saat si senior sengaja menyenggol bahuku—koridor ini memang sempit dan hanya bisa dilalui tiga orang bertubuh normal—dan aku yakin sekali melihat dia menyeringai kepadaku, tadi. Keberanianku membenturkan pintu ke mukanya hilang begitu saja, digantikan ngeri saat si teman cowoknya pun ikut melirikku. Tatapan mereka sama, tajam, menusuk dan mampu menggetarkan bulu romaku. Aku baru merasakannya sekarang, mungkin karena arena latihan gelap waktu itu, penerangan di sini memang agak lebih baik dibandingkan tempat itu. Aku terlalu terpaku pada tatapan mereka sampai tak sadar sesuatu menahanku supaya tidak jatuh saat tubuhku terdorong.
Aku baru sadar saat menoleh setelah mendengar sebuah teriakan yang kuperkirakan adalah milik si senior. Alih-alih sosok wanita kejam itu yang kulihat, wajahku malah membentur sesuatu yang keras—aku rada trauma dengan tragedi mukaku tertubruk pintu kamar—tapi tak sekeras kepalaku yang tetap berusaha memanjangkan leher untuk menengok si senior. Sebuah tepukan membuatku tersadar akan eksistensi mahluk di belakangku yang saat kutatap, ternyata adalah cowok cantik itu. Aku baru mau membalikan badan menghadapnya tapi dia menahan bahuku.
"Ayo kuantar ke kamarmu, cepat!" tukasnya sebelum aku mengajukan protes.
Dia mendorongku pelan, tapi itu cukup membuatku terhuyung kedepan. Rasanya gerakanku melambat dan sebuah kalimat terbentuk cepat di kepalaku, aku akan jatuh! Aku akan jatuh! Di detik terakhir sebelum aku jatuh, kurasakan sesuatu menggapai belakang kaosku.
"Ceroboh!" kesal cowok itu setelah menarikku dan menahanku sebelum tubuhku menerjangnya yang kubalas dengan kekesalan juga.
"Tenagaku sedang tidak ada, dan kau seenaknya mendorongku begitu!" Itu kukatakan secepat mungkin sampai aku sendiri heran, refleksku membalas celaan dari dia lebih cepat dari pada refleksku menghindari serangan.
Semua kembali normal kecuali tanktop-ku yang terlihat karena kaosku tertarik sedemikiam rupa sampai kukira kain putih tipis itu robek. Tangannya diletakkan di bahuku, dia kembali mendorong kendati sekarang masih tak melepaskanku. Kami berjalan beberapa meter, aku menurut saja dikendalikan olehnya, apalagi saat aku hampir terjengkang lagi ketika dia menarik bahuku—menyuruhku berhenti— sementara kakiku masih berpacu. Dia menunjuk sebuah ruangan berpintu besar yang ternyata adalah kamar mandi, lalu berkata, "Pergilah ganti baju."
Aku menurut lagi, mengganti baju dengan pemberiannya, lalu menguncir sebagian rambut dengan potongan kain yang kuambil dari kaos lamaku. Tak lupa juga, aku mencuci wajah dan tangan. Saat aku bercermin, aku bahkan masih bisa menemukan bercak darah di mukaku yang sambil berdecak, aku bersihkan walau setelah itu, aku masih saja terlihat jelek. Saat aku keluar dari sana, cowok cantik itu tengah menyandar di dinding koridor, matanya menatap lempengan besi bergambar tengkorak yang tergantung di pintu masuk kamar mandi. Kutebak, itu adalah ulah anak-anak berandalan yang sudah terlalu bosan memukuli samsak karena di balik gambar tengkorak itu, kulihat beberapa huruf yang dulunya mungkin membentuk kalimat, "kamar mandi".
Setelahnya kami melangkah pelan, menyusuri koridor tanpa percakapan. Aku terlalu lelah untuk bertanya, "Apa kita menuju, lift?" Sedangkan dia terlalu kesal untuk memberiku sedikit pencerahan mengenai tujuan kami. Bisa saja, 'kan, kami berjalan ke arah sebaliknya dari lift, dan dia ingin mengantarku dengan loncat dari jendela lalu bergelantungan di atas angin dengan seutas tali yang keluar dari unung jarinya. Aku tak akan terkejut kalau dia benar-benar melakukannya, toh beberapa waktu lalu, aku melihat sendiri dia mampu menyembukan sakitku dengan ajaib. Pada akhirnya semua itu tak pernah terjadi karena tak lama selepasnya, aku bisa melihat lift.
Lift sepi, tidak seperti biasanya. Aku memaksakan diri bertanya kepadanya, dia cuma menunjuk jam hologram di pintu kotak baja yang sudah mulai berderung, entah naik atau turun. Ini jam dua pagi, tak heran di sini lenggang nan damai, cukup menguntungkan bagiku yang kini tengah lemas bersandar ke dinding seraya membayangkan segelas susu hangat dan roti tawar dengan selai kacang—aku tak harus berdesak-desakan dengan penghuni asrama lain. Tak sampai satu menit, lift akhirnya berhenti di lantai empat belas yang kutahu adalah kantin.
"Kau cukup baik untuk memberi makan orang disorientasi ini," kataku saat kami keluar dari lift.
"Kau sepertinya tidak cukup disorientasi sampai bisa tahu ini kantin," sahutnya sarkas. "Kita perlu langsung ke kamarmu."
Memang dasar dia tidak bisa melihatku senang sedikit saja. Aku menarik tangannya saat dia berbalik, yang mana membuatku malah tertarik olehnya. Aku menubruknya, dan dia yang tak siap, terdorong sampai terjatuh lalu ditimpa oleh tubuh lemasku. Mengabaikan serangkaian pengabsenan hewan yang dilakukan oleh cowok di bawahku ini, aku berucap pelan, "Aku butuh makan, atau kau harus menggotongku ke kamar."
Dia akhirnya mengizinkanku makan. Aku cuma bisa menemukan dua roti gandum keras, dan juga tiga buah kurma kering di stand makan. Aku juga harus menyisihkan sedikit waktu untuk merebus air minum, selain untuk menghangatkan badan di suhu yang rendah ini, aku juga harus rela mencelupkan roti keras itu ke air hangat agar bisa menelannya dengan baik. Aku makan sambil menatap iri cowok cantik itu, dia tengah melakukan sesuatu dengan hologram yang dipancarkan dari hand band-nya. Sudah menjadi rahasia umum kalau semakin tinggi level kami di akademi ini, semakin banyak pula fasilitas yang bisa didapatkan. Melihatnya punya benda itu, aku sedikit paham kalau levelnya ada di atasku dan itu memberiku peringatan untuk tidak mencari masalah dengan dia.
Sekitar 15 menit aku makan, kami melanjutkan perjalanan menuju kamarku. Sebenarnya kalau dari sini, aku sudah tahu kemana arah menuju kamarku sendiri, tapi entahlah, aku ingin dia tetap menemaniku karena sejauh ini aku tak pernah punya teman. Saat kami berjalan sejajar, sesuatu yang hangat terasa di hatiku dan itu cukup membuatku ingin menghembuskan napas lega lalu berteriak, "Seperti inikah rasanya punya teman?!" Tapi itu tak kulakukan karena teringat tatapan mematikan cowok itu yang mirip malaikat maut walau sekali lagi kutegaskan, aku tidak pernah bertemu mahluk macam itu.
Saat sampai di depan pintu kamarku, aku menatapnya dengan polos, apalagi saat sia menyuruhku lekas masuk. Membenamkan pertanyaan yang terlintas dalam otakku, aku menarik tangannya sebelum dia pergi—beruntung tidak terjadi acara tubruk-menubruk lagi—lalu bertanya, "Siapa namamu?"
Dia menatapku jengah, menyentak tanganku dengan kasar. Dia berlalu setelah mengucapkan satu kata dengan suara beratnya yang mampu membuatku tersenyum macam orang gila.
"Orion, namanya Orion," ucapku mendadak lupa dengan perlakuan kasarnya dan lemparan kaus dengan polusi aroma yang mampu memancing cairan lambungku untuk naik ke mulut.
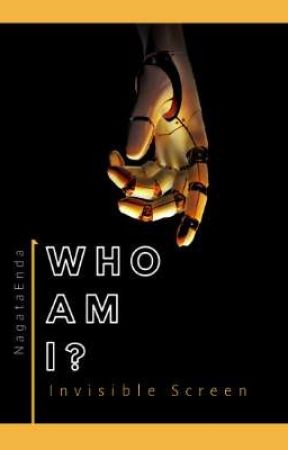
YOU ARE READING
Who Am I? Invisible Screen
Science FictionNamanya menjadi sependek potongan sosis di kantin. Dia tak punya keluarga, apalagi marga. Pulangnya bukan kembali ke rumah hangat yang ramai akan anggota keluarga, tapi naik lift kemudian masuk ke kamar yang cuma 3x4 meter luasnya. _________________...
