Aku tidak tahu apa yang direncanakan alam, tapi semenjak "penculikan" yang kulalui bersama Orion dan si rambut merah yang sampai saat ini belum kutahu namanya, aku jadi lebih sering bertemu dengan mereka. Di kantin, di gelanggang, di lift, bahkan Orion tahu-tahu ada di kelas yang sama denganku keesokan harinya.
Aku harus menahan diri untuk menginterogasi kenapa dia bisa nyasar ke sini karena pemateri kelas sudah datang sambil memelototkan mata melihat kesemrawutan tempat ini. Alasan lain adalah karena aku butuh segera duduk setelah didepak dari lift oleh sekumpulan lelaki bertumbuh gempal yang sepertinya mau berkelahi di dalam sana. Aku sampai harus lewat tangga karena kebetulan kelasku cuma tinggal satu lantai lagi dari tempat pemecatanku sebagai penumpang kotak besi itu, aku juga malas menunggu lift selanjutnya. Kakiku jadi lelah karenanya (aku memang sepayah itu).
Aku tidak bisa fokus mendengarkan penjelasan guru di depan mengenai sebuah kumpulan angka yang tertulis acak-acakan di papan tulis. Dalam jadwal pelajaran, kelas ini disebut sebagai kelas matematika. Akan tetapi siapa yang perduli dengan itu ketika sang guru yang menjelaskan saja tampak jengah sendiri dengan apa yang dia jabarkan. Barangkali dia sudah mengulang materi itu ribuan kali sejak dia direkrut sebagai pengajar di tempat ini.
Aku sendiri, sedang sibuk menatapi lantai sambil sesekali tersenyum edan. Pemuda jakung berambut panjang di depanku lah yang membuatku begini. Aku masih ingat apa yang dikatakannya di malam (pagi buta) saat dia mengantarku. Seakan fakta akan namanya yang membuatku mesem-mesem belum cukup menggelikan, dia kembali lagi bahkan saat aku masih menempel di pintu lalu mengatakan sesuatu yang membuatku makin gila.
"Melihatmu kesepian sampai mengira pintu yang kau peluk itu adalah pacarmu, aku berbaik hati menawarkan diri menjadi temanmu. Mulai sekarang kita berteman dan aku tidak menerima penolakan," katanya dalam sekali tarikan nafas.
Selepas mengatakan itu, dia pergi begitu saja. Meninggalkanku terpaku sambil menggeratkan pelukan ke pintu dan melayangkan ingatan ke novel lawas yang kubaca di meja informasi umum asrama. Tempat itu cuma sepetak ruang yang diisi sembilan belas meja pemancar hologram yang bebas dipakai kapan saja oleh penghuni asrama. Aku yang sedang iseng mencari informasi tentang cara menembak dengan benar, tanpa sengaja menemukan e-novel yang judulnya amat menggelikan, membuatku ingin membacanya. Ada satu kalimat yang dikatakan tokoh lelakinya yang kuingat dengan jelas, "Mulai sekarang kau jadi pacarku, tidak ada penolakan!" yang lantas membuat sang gadis lawan bicaranga mematung—hal yang kulakukan juga malam itu.
Kelas selesai saat bel terdengar nyaring ke sepenjuru gedung.
"Orion!" panggilku mencoba menarik perhatian cowok yang mulai melangkah keluar kelas itu.
Aku berniat mengajaknya bicara selepas sekolah, tapi dia bahkan tidak menoleh sedikit pun saat kupanggil. Sebuah kesialan lagi-lagi menghampiriku ketika aku bangun dan mengambil ancang-ancang untuk mengejarnya, aku malah terjatuh mengenaskan ke lantai, beruntung kepalaku tak terkena meja ataupun kursi.
"Sialan!" makiku saat melihat tali sepatuku yang terikat ke kaki meja. Tanpa perlu berfikir dua kali, aku langsung tahu siapa pelakunya. Sophie, gadis kecil pirang super jahil pastilah yang melakukannya karena sejak pelajaran tadi, dia berbaring di koridor meja tanpa perduli penjelasan guru di depan sana. Aku bahkan sempat melihatnya melakukan hal serupa pada temanku yang lain, tapi, aku tidak sadar dia melakukan itu juga padaku. Seharusnya temanku yang lain itu akan jatuh juga sep—
Bruk!
... sepertiku, lanjutku dalam hati.
Dia terjatuh dengan tidak etis ke lantai. Aku menatapnya, dia pun menatapku membuat gerakanku melepas tali dari kaki meja terhenti.
Kelas ricuh dengan tertawaan dan cemoohan untuk si algojo kelas yang baru saja terjatuh cuma gara-gara gadis pirang—yang dikawal oleh algojo kelas lain. Cuma perlu menunggu beberapa detik sampai sebuah kursi melayang hampir mengenai si pirang kalau saja pengawalnya tidak sigap menarik tubuh yang bahkan tak lebih dari 145 cm tingginya itu. Tatap-menatap antara kami selesai, karena aku sedang menatap ngeri sebuah penyok besar di meja yang akhirnya tersasar lemparan kursi. Tanganku lanjut melepas tali sepatuku.
"Kau punya masalah dengan kami, bung?!" ucap pengawal itu.
"Tanyakan saja pada tuan putrimu itu!" Alih-alih melepas tali sepatu, dia malah melepaskan kakinya dari sepatu itu. Kulihat dia bangkit lalu berjingkat keluar kelas, tapi sebelumnya dia berkata, "tunggu saja lemparan kursi selanjutnya, bocah ingusan!" sambil memaut tatapan kami lagi.
"Cih! Cuma Zie si gadis kecil yang ...." Aku tidak sempat mendengarkan ocehan lanjutan dari bocah itu karna selanjutnya, aku menemukan diriku sedang mengangkat kursi baja dan melemparnya ke arah dua manusia di sudut ruangan.
Mereka memasang tampang terkejut kendati lemparanku tidak mengenai mereka. Penghuni kelas mengira aku cukup murah hati untuk tidak menggencet mereka dengan baja berbentuk kursi itu dan cuma berencana menggertak, tapi kenyataannya, lemparanku memang benaran meleset.
"Siapa yang kecil di sini, tuang putri?!" tanyaku dengan suara direndahkan. Sekalian saja aku bersikap seperti gadis baik yang meluapkan kemarahan dengan elegan padahal melempar kursi bukan perbuatan tidak termasuk ke dalamnya.
Kulihat gadis itu terkesiap melihatku yang notabenya tidak pernah berulah di kelas berani mengintimidasi mereka. Aku pergi setelah menatap seisi ruangan dengan congkak. Orion sudah tidak ada saat aku keluar kelas, dia barangkali langsung ke kantin karena ini sudah jam makan malam. Sehabis itu, kami harus menjalankan latihan rutin seperti biasa.
Aku berjalan pelan ke arah lift, hampir mustahil bagiku buat mencarinya di tempat yang luas itu tanpa harus menaiki salah satu meja lalu kesetanan memanggil nama Orion. Aku bahkan tidak tahu dia makan di kantin bawah atau atas. Setelah pertimbangan yang sama sekali tidak matang, aku akhirnya memutuskan buat pergi ke kantin atas untuk menyingkat waktu karena omong-omong, kelasku di lantai paling atas. Kebanyakan kelas di lantai ini adalah kelas yang isinya bocah-bocah dablek dan bodoh, aku masuk kategori bodoh.
Mau lihat buktinya?
Bruk!
Aku terjatuh ... sebab lupa tak mengikat lagi tali sepatuku. Aku ... memang bodoh. Beruntung tidak ada yang melihat kekonyolanku setelah sebelumnya aku belagak keren di kelas.
"Bodoh!" Garis kebodohanku diperjelas lagi oleh orang yang entah siapa, dia berdiri di depanku dengan tangan tersodor—aku tidak sempat menyorot wajahnya.
"Bangunlah," perintahnya. Aku menurut, meraih tangannya yang mampu menenggelamkan tanganku dengan rasa hangat lalu dia menarikku berdiri. Aku terperangah sendiri saat mendongak melihatnya. Dia Orion.
"Kau." Aku mengambil satu langakah mundur, mataku memindainya dengan teliti. Dia masih memakai kaos abu-abu seperti yang kulihat di kelas, tingginya masih sama seperti yang kuingat, dan wajahnya pun masih lebih cantik daripada aku, padahal akulah yang perempuan di sini. "Suaramu, kau punya koleksi pita suara ya?" tanyaku penasaran.
"Mana ada." Suaranya masih terdengar lain dengan yang kudengar semalam.
"Suaramu agak berbeda," ucapku.
Dia terdiam beberapa saat, entah apa yang dipikirkannya. Kami terhanyut dalam diam sampai dehamannya mengagetkanku, dia melakukan itu beberapa kali sampai merasa dahak ditenggorokannya hilang, dia kembali bersuara, "sudah. Sudah sama lagi, 'kan?" tanyanya.
Aku langsung menyesal saat itu juga, suara baritonnya kembali dan kewarasanku yang menghilang. Aku ingat, aku tak semerinding ini saat mendengar suaranya semalam, itu terjadi sejak ... dia menyebutkan namanya. Aku jadi ragu, yang membuatku sebegini terpengaruh oleh Orion itu, suaranya atau fakta kalau namanya begitu kusuka. Kami jadi diam lagi. Yang terdengar cuma ajakannya ke kantin yang kujawab dengan anggukan kepala. Saat di kantin pun kami sesunyi malam, walau secara harfiah tempat ini penuh dengan hingar bingar manusia.
Kebekuan ini terjadi lama, sampai manusia ceking berambut merah datang mengacaukan makan malam kali ini.
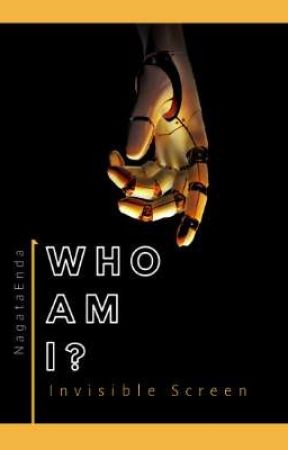
YOU ARE READING
Who Am I? Invisible Screen
Science FictionNamanya menjadi sependek potongan sosis di kantin. Dia tak punya keluarga, apalagi marga. Pulangnya bukan kembali ke rumah hangat yang ramai akan anggota keluarga, tapi naik lift kemudian masuk ke kamar yang cuma 3x4 meter luasnya. _________________...
