"Sssshh."
Lidahku sakit!
Aku meringis. Kupikir bisa menahan sakit dengan menggigit lidah. Ternyata, itu tindakan bodoh, memperparah keadaan. Rambut kaku menusuk-nusuk leherku, suaraku tertahan di tenggorokan saat bersiap mengumpat. Bila saja tidak dalam kesakitan separah ini, aku ingin mencincang tubuh lelaki berrambut merah di sampingku.
Sebisa mungkin aku mengabaikannya, tak ingin menambah beban dengan berfikir: kenapa ini terjadi? Sungguh pertanyaan kosong yang tak berguna. Lagi pula kalau pun aku tahu jawabannya, maut belum tentu meloloskanku.
Sempat terlintas pikiran untuk meminta tolong. Tapi mengingat untuk mengumpat sekata saja, aku tidak bisa, pastilah aku tak akan mampu aku mengucap 'tolong'. Maka gugurlah rencana itu, meninggalkan kekecewaan yang bercokol di hatiku. Dadaku makin sesak. Cowok disampingku—yang menjadikanku bantal guling hidupnya—masih dengan nyaman mendekapku erat. Mempersempit kesempatan oksigen untuk mengunjungi paru-paruku.
Cowok rambut merah itu terus bergerak, mengusal leherku. Dalam hati aku mengumpat dan tentu saja tidak ada yang berubah kecuali mukaku yang semakin mengkerut menahan nyeri dan mataku yang semakin berair. Dengung statis meraung-raung dalam kepalaku, mengacaukan orientasiku terhadap sekitar, semua mulai terasa abstrak.
Langit-langit dan dinding membesar, kemudian mengecil dalam sedetik. Ranjang yang kutempati seperti undur diri, membiarkanku terombang-ambing dalam ketidakmampuan melawan sakit. Untuk sesaat, kukira aku akan benar-benar mati. Terbukti saat sebuah sentakan keras menerjang tubuhku. Lalu sebuah bayangan menjulang tinggi menghalangi seberkas cahaya dari belakangnya. Diakah malaikat maut?
Sesuatu menangkup tengkukku, menyebarkan sensasi menyengat kulit. Yang paling melegakan, sakit itu hilang tak bersisa. Mengembalikan akal sehat yang sempat hilang. Banyak pertanyaan-pertanyaan membanjiri kepalaku: apa aku benar-benar mati? Apa orang meninggal bisa merasakan sakit?
Aku membuka mata—masih ruangan putih yang menyambutku. Langit-langit diatas sana terlihat kokoh, tidak lagi bergerak liar. Dan walau tubuhku lemas seakan lupa cara bergerak, aku sudah bisa melihat jelas. Apalagi sekedar melihat mahluk yang sedang duduk di pinggir ranjang. Dia menunduk, membiarkan rambut agak panjangnya menutupi wajah.
Aku hampir saja melayangkan tendangan ke arahnya karena kukira dia hantu, tapi kusadari alasan hilangnya sakit itu, karena tangannya yang ditangkupkan di tengkukku. Oh, dia penolongku, atau ... dia malaikat maut yang ingin mencabut nyawaku? Saat dia mendongak, wajah jelita yang kulihat—apa malaikat maut perempuan? Wajahnya datar menahan kantuk, dia menatap malas kearahku—apa malaikat mau butuh tidur?
"Zie konyol!" gumamku memaki diri. Mudah sekali termakan omongan cewek gila yang kutemui minggu kemarin yang bilang masalah pencabutan nyawa.
Napasku memburu saat mata sayu itu menatapku. Eh! Napas? Aku masih bernapas—aku masih hidup!! Aku bisa saja melompat girang sembari berjoget ria andai saja tubuhku tidak lupa cara bergerak. Mengabaikan adegan bar-bar yang bisa saja benaran kupraktekan, aku kembali fokus ke masalah yang kuhadapi sekarang ini. Aku terbangun di kamar fox lain—walau dari tadi setengah teler, aku masih bisa menyadari kalau tata letak kamar ini sama dengan kamarku, jadi kusimpulkan kalau aku masih di akademi—dengan seorang cowok dan perempuan di dalamnya. Setahuku, satu kamar hanya boleh dihuni oleh satu orang. Apakah mereka salah satu fox pembangkang yang sedang berpacaran sembari menculikku? Atau mereka menculik sambil berpacaran?
Remasan pelan di tengkukku mengembalikan atensiku ke si penolongku. Sengatan kecil yang tadinya menyakitkan, kini berganti hangat yang menyenangkan.
"K-kenapa?" tanyaku yang lebih seperti suara tercekik. Aku perlu berdeham beberapa kali sebelum akhirnya memutuskan bersuara lagi, "Ada apa?"
Dia cuma menggeleng. Cewek aneh, batinku sambil mengusap ingus dengan tangan kemudian mengelapnya ke sprei kasur. Kupikir dia tidak akan perduli denganku, tapi nyatanya dia berkomentar dengan ringan.
"Jorok," celanya.
Sementara mukanya mengerut jijik, aku malah tercengang mendengar suaranya yang berat dan ... maskulin? Telingaku mungkin salah dengar tapi mulutku dengan kurang ajar berkata, "Kau itu cewek atau cowok sih!"
Sesaat setelah mengatakan itu, aku merasa kalau umurku tinggal hitungan detik. Wajahnya terlihat ingin menelanku hidup-hidup. Percayalah, mukanya lebih menyeramkan dari si rambut merah yang sekarang baru kucemaskan nasibnya setelah dibanting oleh cewek—orang—di depanku ini. Tangannya meremas tengkukku, menggetarkan bulu roma di seluruh tubuh. Sial ... itu geli!
Dengan tatapan sengit, dia menjawab, “Cowok!”
Kulihat tangannya menyugar rambut kebelakang. Bukannya terlihat keren atau mengesankan, dia malah membuat surainya semakin berantakan—beberapa yang tidak terlalu panjang terjatuh lagi di dahinya. Dia menghujamku dengan mata tajamnya. Bibirnya terkatup rapat, dan aura gelap di ruangan ini makin pekat dan yang bisa kulakukan cuma ... panik.
Lima detik berlalu dengan sangat lambat. Seakan mengejekku yang ketakutan di bawah tatapan itu. Lagipula, di mana letak kesalahku? Mana aku tahu kalau sebenarnya dia itu cowok. Salahkan saja wajah cantik dan rambut panjangnya.
Di tengah ketegangan itu, sesuatu seperti kain—entah darimana—mendarat tepat di wajahku.
"Pakai itu," perintahnya.
Aku tentu tidak akan menolak pemberiannya kalau saja gumpalan kain itu tidak bau kecut bercampur aroma maskulin yang entah kenapa terasa memuakkan. Aku menjauhkan benda itu dari radar penciumanku.
“Bau!” Terkutuklah mulutku yang tidak punya rem. Wajahnya makin menyeramkan sekarang, membuat panik kembali menyerangku.
Kami bertatapan beberapa saat, saling melempar tatapan kesal, tapi, akhirnya aku mengaku kalah juga. Kutahan napas, lalu dalam satu gerakan mengusap semua cairan menjijikan nan lengket dari wajahku. Setelahnya, kulempar kaos itu. Sebenarnya aku menargetkan wajahnya, tapi meleset.
“Coba kau cium sendiri baunya! Dan berhenti memasang wajah menyeramkan itu. Aku takut.” Suaraku mencicit di akhir kalimat. Kututup wajahku dengan telapak tangan lalu beseru, “aku tidak mau melihatmu!”
“Cewek tidak tahu diri!” Aku diam saja mendengarnya. Dia benar, aku ‘kan memang tak pernah tahu diri.
Lagipula aku lebih tertarik dengan erangan yang terdengar bersamaan dengan umpatan penambah koleksi kata kasarku. Aku duduk, lau mengintip, ternyata Si Rambut Merah yang mengumpat. Dia yang tengah tidur di lantai rupanya terganggu oleh lemparan kaos bau plus lembab bekas ingusku.
Aku bergidik jijik, saat kutilik cowok penyelamatku, ekspresinya sudah lebih bersahabat. Dia tengah menoleh menatap ke arah pintu, entah apa yang menarik dari benda itu. Aku kembali menutup mata saat dia menoleh kemari. Dengusan jengah terdengar.
“Buka matamu,” titahnya datar.
“Aku tidak mau melihatmu!” Aku masih keras kepala, menutup muka dengan tangan.
“Kau pikir apa yang kau lakukan tadi? Buka mata dan pergilah." Dia berbalik membuka pintu lemari dengan kasar lalu sedetik kemudian, sebuah kain hinggap lagi di kepalaku. "Ganti di kamar mandi, dan lekas ke kamarmu!"
Nah, sudah kubilang, ini memang masih di akademi.
Cuma itu yang dia katakan sebelum menyeretku bangun lalu dengan kejam mendepakku keluar dari kamarnya. Dia bahkan tidak perduli saat aku terjatuh di koridor karena tak mampu menahan bobot tubuh. Entah berapa lama aku pingsan di kamarnya, yang pasti, aku merasa sudah tak makan berminggu-minggu sampai bisa selemas ini. Lagipula, dua cowok itu niat menculikku tidak, sih! Mana ada penculik yang melepas korbannya begitu saja. Dan mana ada pula korban penculikan yang malah kesal saat dilepaskan.
Setelah memastikan kain itu tak berbau apak, aku menyingkirkannya dari mukaku. Butuh banyak tenaga untukku berdiri mantap. Kutatap sejenak pintu kamar dua cowok menyebalkan itu, berharap salah satu dari mereka bisa mengantarku ke kamarku karena, aku bahkan tidak tahu ini di lantai berapa. Lama menekuri pintu bercat putih itu, dan demi kelangsungan hidup benda persegi panjang itu, aku akhirnya memilih mengalihkan pandangan. Jangan sampai aku dengan tenaga yang masih timbul tenggelam ini menghancurkannya.
Aku baru saja mengalihkan pandangan, mengira-ngira, lift ada di ujung yang mana. Tapi, entah dosa apa yang telah kuperbuat di masa lalu, netraku bertubrukan dengan kelereng hitam penuh sorot kebencian milik seorang cewek berjaket kulit hitam yang tengah berjalan ke arahku, dengan ditemani seorang cowok berperawakan tinggi. Aku mendadak ingat apa yang terjadi sebelumnya, sebelum aku terdampar di ruang antah berantah bersama dua cowok aneh. Dia ... senior perempuan itu ....
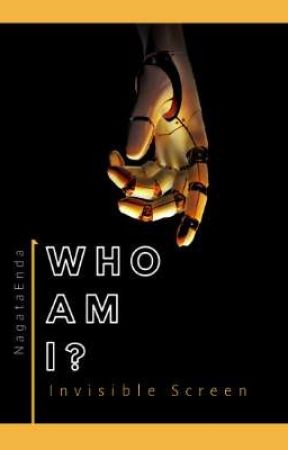
YOU ARE READING
Who Am I? Invisible Screen
Science FictionNamanya menjadi sependek potongan sosis di kantin. Dia tak punya keluarga, apalagi marga. Pulangnya bukan kembali ke rumah hangat yang ramai akan anggota keluarga, tapi naik lift kemudian masuk ke kamar yang cuma 3x4 meter luasnya. _________________...
